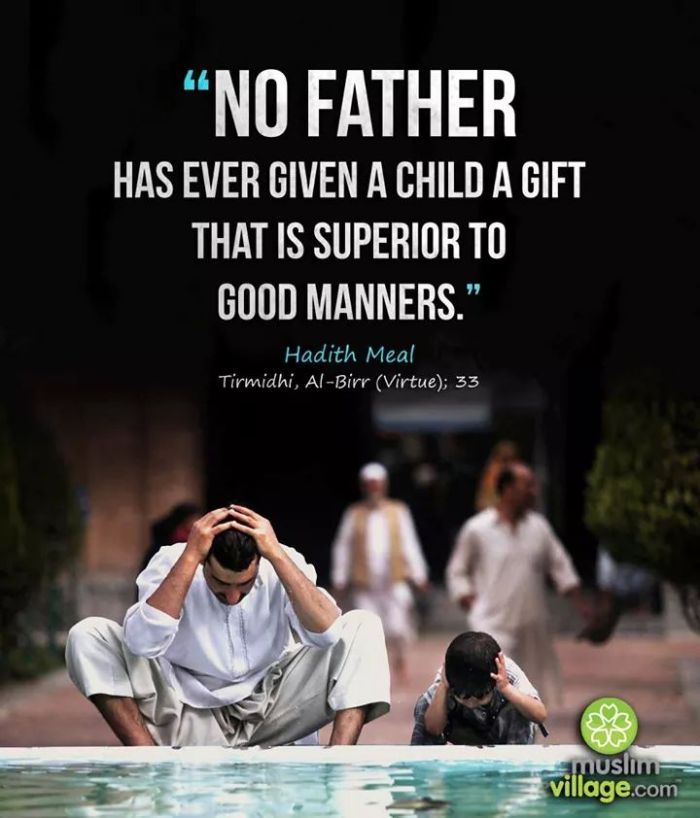Alhamdulillah, suka sekali dengan surat satu ini. Isi suratnya mengatakan, bahwa agar aku tak merugi = aku harus beriman + beramal shalih + saling menasihati dalam kebaikan + saling nasihati dalam kesabaran. Semuanya harus lengkap. Tak boleh ada yang kurang satu pun. Inilah salah satu surat yang membawaku ke perjalanan yang cukup panjang, meninggalkan kesan mendalam sampai sekarang dan entah sampai kapan nanti.
Aku menebak-nebak, sepertinya al-‘Ashr membagi manusia menjadi tiga golongan. Golongan pertama adalah mereka yang tak mempedulikan arahan ini sama sekali –a’udzubillah. Golongan kedua adalah mereka yang tak mau merugi, tapi berhenti sampai di situ. Ketidakmaumerugian mereka baru sampai itikad dalam hati dan lisan saja, tak lebih. Adapaun golongan ketiga adalah mereka yang punya itikad dalam hati bahwa mereka tak mau merugi. Mereka pun berusaha dengan sungguh-sungguh agar tak masuk ke dalam kelompok orang yang merugi.
Aku memutar isi kepala agar aku masuk ke golongan ketiga. Mengingat, dalam lingkar individu, imanku naik-turun. Bahkan terkadang lebih banyak turunnya. Amal shalihku pun minimalis dan banyak celanya. Entah itu di niat yang belum murni, tersusupi ujub, dan cela-cela lainnya. Dalam radius yang lebih luas, amal sosialku pun terlalu biasa-biasa saja. Aku sering merasa sungkan untuk tawaa shaubil haq dan tawaa shaubish shabr. Kenapa? Kembali lagi ke lingkar individuku tadi.
Berangkat dari sini, aku mencoba membuat formulasi-formulasian berdasarkan sedikit ilmu yang ku ketahui. Fokus pertamaku adalah meningkatkan iman dan membuat sesuatu yang bisa berfungsi sebagai ‘shockbreaker’. Sebagaimana fungsinya pada sepeda motor, ‘shockbreaker’ iman ini harus bisa memantulkan keatas kembali imanku yang sempat turun. Fokus keduaku adalah menemukan cara agar dalam 24 jam aku bisa melakukan kebaikan dengan kuantitas dan kualitas yang keren. Juga meminimalisasi tindak lalai sampai ke angka nol. Dan ini harus menjadi habit.
Guruku mengatakan, iman itu naik turun, naik karena melakukan ketaatan. Turun karena melakukan kemaksiyatan. Maka dalam hal ini, langkah yang perlu aku lakukan adalah meninggalkan kemaksiyatan secara revolusioner –karena kalau sedikit-sedikit, nanti malah kembali dilakukan. Kemudian membangun habit dalam beramal shalih secara bertahap –karena kalau sekaligus, nanti cepat bosan. Aku memulainya dengan membuat daftar amal buruk/maksiyat yang biasa aku lakukan. Mulai dari kelas berat sampai kelas berat banget! –karena tak ada istilah dosa/maksiyat kelas ringan kalau melihat kepada Siapa aku berdosa dan melihat keadilan-Nya.
Aku tulis deh satu per satu. Mulai dari mengaakhirkan berangkat shalat berjamaah, tidak menundukan pandangan, ceplas ceplos, suuzhan, menunda-nunda pekerjaan, kurang tepat janji, ujub, sombong, dan begitu seterusnya. Itu semua harus ku tinggalkan secara revolusioner. Setelah itu aku pun coba membuat daftar kebaikan apa saja yang secara bertahap harus aku jadikan habit. Aku memulainya dari yang wajib dulu, kemudian yang utama, dst. Dan, tahukah kamu apa yang terjadi? Ternyata itu semua tak semudah yang ku bayangkan. Aku gagal, terus pesimis, dan ini terjadi berulang berkali-kali. Sampai akhirnya aku bertanya-tanya, di mana letak kesalahanku, apa pada prioritas, atau memang akunya saja yang payah kurang istiqamah?
Sedikit demi sedikit aku menemukan jawabannya: Aku harus menemukan kunci perbaikan diriku. Aku harus menemukan sesuatu, yang apabila aku menjadikannya kebiasaan dan menjaganya mati-matian, maka ia akan membawa perubahan secara signifikan pada amal lainnya. Sesuatu ini bekerja seperti poros roda. Saat ia berputar, berputar pula seluruh bagian rodanya. Aku teringat dengan teorinya Mas Charles Duhhig dalam buku the Power of Habit, beliau mengatakan sebetulnya dalam diri seseorang, juga dalam sebuah organisasi/perusahaan, ada aktivitas kunci yang apabila itu dijadikan kebiasaan maka akan membawa perubahan signifikan pada aktivitas-aktivitas lainnya. Teorinya ini berangkat dari penelitiannya atas beberapa perusahaan di Amerika yang mereka berhasil keluar dari krisis setelah melakukan perbaikan di aktivitas-kebiasaan kunci mereka. Tentunya ini diawali dengan menemukan habit kunci tersebut. *Insya Allah nanti aku akan buat tulisan khusus terkait teori ini. Karena terlalu panjang kalau aku ceritakan di sini.
Maka pertanyaan berikutnya adalah apa ya yang bisa/harus aku jadikan habit kunci? Aku coba mencari dan mencari berhari-hari. Akhirnya sampai saat ini Allah baru menunjukiku dua hal ini:
1. Apabila hati seseorang baik, baik pula seluruh tubuhnya.
2. Apabila shalat seseorang baik, baik pula amal lainnya.
Sesuai dengan hadits:
Dari An Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung).” (HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599).
Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Apabila shalatnya baik maka seluruh amalnya pun baik. Apabila shalatnya buruk maka seluruh amalnya pun akan buruk.” (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mujamul Ausath, II:512, no. 1880)
Senang sekali rasanya ditunjukki-Nya hal ini. Ternyata teori kebiasaan kunci itu sudah ada sejak zaman dulu loh. Bahkan Islam menempatkannya pada hal yang sanagat fundamental ini. Ini pasti obat yang mujarab. Karena Rasulullah yang langsung menyampaikan. Bertolak dari sini, saat itu akhirnya aku putuskan untuk memulai perbaikan iman dan amal dari dua hal ini: memperbaiki hati (bathin) dan memperbaiki shalat (zhahir).
Dengan bismillah aku mulai mencari tahu apa itu hati, apa perannya, apa yang ia suka, apa yang ia benci, apa makanan bergizi untuknya, apa penyakit yang bisa menjangkitinya, apa obatnya bila ia sakit, dan seterusnya. Dalam waktu yang sama aku pun mencari tahu perkara shalat. Aku jadi bertanya-tanya, sebetulnya apa yang menjadikan shalat punya kedudukan begitu tinggi dibanding amal lainnya –padahal kalau dilihat dari pengorbanan yang harus dikeluarkan, agaknya menahan haus lapar saat puasa, mengeluarkan uang untuk zakat, dan beribadah haji lebih banyak pengorbanannya ketimbang shalat. Jangan-jangan pandanganku terhadap shalat selama ini salah. Lantas bagaimana dong shalat yang baik itu, hal apa yang bisa merusak shalat, bagaimana agar shalat khusyu’ dan terasa lebih hidup, dan begitu seterusnya. Sampai sekarang dua hal ini terus aku dalami-renungi dengan bertanya kepada guru-guruku, dengan menyimak rekaman-rekaman audio/video kajian, juga membaca buku-buku seputarnya.
Bagaimana pengamalannya? Aku menaruh ukuran apakah hatiku sudah sehat dan shalatku sudah baik dari apa yang aku bisa rasakan secara langsung. Yaitu pada shalatku. Kenapa? Karena ukuran baiknya shalat ada pada khusyu’nya. Sementara khusyu’ itu letaknya dalam hati. Khusyu’ pun jadi manifestasi tertinggi dari sehatnya hati –kalau kata Said Hawa mah begitu. Aku lihat deh, apakah aku sudah shalat berjamaah di awal waktu atau masih menunda-nunda berangkat ke masjid? Apakah saat shalat aku masih kepikiran hal lain selain Allah atau bagaimana? Apakah perhatianku terhadapan perbaikan internal dan eksternal yang dimulai dari bersih-bersih hati dan perbaiki shalat sudah berpengaruh signifikan ke peningkatan iman dan amal yang lainnya? Dari sudut inilah aku mengukur perkembanganku dalam mengamalkan “illalladziina aamaanuu wa ‘amilush shaalihaati”.
Selang beberapa pekan aku mempraktekan formulasi-formulasianku tadi, aku pun melihat polanya. Ternyata kondisi hati yang baik (ingat Allah, merasa dilihat terus sama Allah) sangat memengaruhi seberapa bersungguh-sungguh aku menjadikan shalatku dan amal yang lainnya berkualitas. Kemudian seberapa baik shalatku itu sendiri ternyata benar-benar pengaruh ke seberapa baik aku menjaga janji, tepat waktu, disiplin, tidak menunda-nunda, dan bahkan hal kecil seperti menjaga kebersihan. Bahkan, benar kata AaGym, aku bisa melihat bagus tidaknya shalatku dari kebersihan tempat tinggalku. 😀
Di samping itu, selama beberapa pekan itu aku pun menemukan hal lain yang tak kalah menarik. Yaitu soal titik lemah yang dari arah sana hatiku mudah terinfeksi kuman-kuman maksiyat. Kemudian kuman-kuman maksiyat ini membuat imanku terganggu, jatuh sakit, dan amal shalihku lumpuh. Sistem kekebalan imanku pun seperti bekerja mencari titik lemah tersebut sekaligus mencari solusinya. Tahukah kamu di mana letaknya? Jujur, aku sendiri sulit menemukannya. Sampai sekarang masih meraba-raba. Apa sih yang biasanya membuatku lalai atau yang biasa membuat hatiku berasa kotor? Karena sulit aku temukan, yasudah aku coba tebak, sepertinya titik lemahku ada pada kurang jagonya aku dalam menjaga lisan, pandangan, dan pendengaran.
Ada sebuah postulat berbunyi begini:
Siapa yang mudah toleran terhadap melakukan kelalaian kecil, maka ia akan mudah toleran juga terhadap melakukan kelalaian-kelalaian yang lebih besar. Sebaliknya, siapa yang sangat menjaga diri dari kelalaian kecil, maka ia akan mudah dalam menjaga diri dari kelalaian-kelalaian besar.
Well, pada akhirnya ku fokuskan perhatianku pada tiga hal ini saja. Aku percaya, kalau aku mudah kebobolan dari arah sini, aku pun akan mudah kebobolan dalam hal-hal yang lebih besar. Aku semakin yakin bahwa aku harus peduli akan hal ‘kecil’ ini setelah melihat sebuah tulisan tentangnya di internet:
“Tidak istiqamah iman seseorang sebelum istiqamah hatinya, dan tidak akan istiqamah hatinya sebelum istiqomah lisannya”(HR Ahmad).
Aku pun bertanya ke Ust. Faris Jihady melalui akun ask.fm/farisjihady tentang maksud dari istiqamahnya lisan. Beliau menjawab, yang dimaksud dengan istiqamahnya lisan adalah
“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam” (HR. Bukhari-Muslim).
Di dalam hati aku berkata, “Tuuh kan, benar. Aku harus menjaga –bahkan sampai– hal ‘kecil’ seperti menjaga lisan yang aku dan sebagian dari kita sering mengabaikannya.” Nah loh. Aku jadi ingat selama ini banyak meracau yang kurang perlu di medsos, whatsapp, atau di tempat lain. *Maaf ya Allah, suring banget kelupaan.
Terkait pandangan, sudah cukup jelas. Apalagi setelah aku baca buku Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang jangan dekati zina. Begitu juga dengan menahan diri dari mendengar yang tak berguna. Maka aku pun harus mengalihkan pandanganku, pendengaranku, juga lisanku kepada sesuatu yang bernilai tinggi. Sehingga mereka tak berminat kepada hal-hal rendah. Aku kembali bertanya-tanya, apa yang bisa menyibukkan pandangan, pendengaran, dan lisanku dari hal yang membawa mudharat dan tidak berguna di atas? Mungkin jawabannya adalah Quran, ilmu, dan amal shalih itu sendiri. Aku jadi teringat dengan tagline Tahfizh Samrt 3 (program tahfizh di IQF),
“Setiap detik harus bernilai, agar kita semakin dekat dengan Allah!”
Aku ingat betul, saat itu aku mengusulkan ini menjadi tagline TS3 karena terinspirasi dari nasihatnya Ust Abdul Aziz Abdur Rouf bahwa seorang yang mau menjadi penghafal Quran hendaknya memerhatikan bahwa aktivitas menghafal Quran itu tujuannya agar kita bisa membaca Quran sebanyak-banyaknya setiap harinya. Seperti para sahabat, tabi’in, dan generasi terdahulu kita. Dan itu tidak akan terjadi kalau mataku lebih banyak tersibukkan oleh medsos ketimbang Quran, lebih banyak mendengar hal tidak penting ketimbang mendengar ilmu, atau hal bermanfaat lainnya. Dengan demikian, aku pun akhirnya menemukan obat pengangkal titik lemahku tadi. Ia pun sekaligus menjadi shockbreaker imanku: Quran (dzikr) dan Ilmu. Quran dan terus menuntut ilmu lah yang insya Allah akan menjaga naik-turunnya imanku dan menyibukkanku dengan amal shalih. Sehingga imanku pun naik-turunnya bisa bergradien positif atau trendnya meningkat (lebih banyak naiknya dibanding turunnya).
Sampai detik ini, seperti itulah perjalananku membersamai surat al-‘Ashr ini. Karena tulisan ini panjang banget dan mungkin berputar-putar hehe, maka aku coba simpulkan ya. Kesimpulan dariku begini:
1. Dua hal pertama yang harus ada padaku agar aku tidak merugi adalah iman dan amal shalih. Adanya iman mengakibatkan lahirnya amal shalih. Iman dan amal shalih ini satu paket. Seperti bunga dan bau harumnya. Dengan beramal shalih iman pun naik. Dengan maksiyat iman terpuruk.
2. Untuk yang imannya lebih banyak turunnya, dan amal shalihnya minimalis sepertiku, ayo bangun! Kita lakukan sesuatu supaya kita tak merugi. Kita cari cara agar iman lebih banyak naiknya. Agar amal shalih terus bertambah dan istiqamah.
3. Menurutku itu semua bisa dimulai dari hal yang mendasar-mengakar dan punya pengaruh besar terhadap hal lainnya. Yaitu, perbaikan hati (bathin) dan shalat (zhahir). Karena apabila hati baik, baik seluruh tubuh. Bila shalat baik, baik seluruh amalan lainnya. Perbaikan pada kedua hal ini akan membawa perubahan baik pada seluruh aspek dalam kehidupan kita.
4. Di samping itu, kita pun perlu waspada terhadap ancaman luar yang bisa melemahkan iman dan melumpuhkan amal shalih kita. Ancaman luar itu akan masuk melalui titik lemah yang pada setiap orang letaknya berbeda-beda. Cara agar iman-amal shalih bisa imun dari ancaman luar adalah dengan menjaga diri dari kelalaian-kelalaian yang sangat mudah diabaikan orang: menjaga lisan, pandangan, dan pendengaran dari yang tidak hak. Kalau terhadap kelalaian ‘kecil’ saja kamu sangat perhatian, maka apalagi terhadap kelalaian yang lebih besar dari itu?
5. Titik lemah tersebut harus ku tutupi. Dengan apa? Menyibukan diri dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri dan mengingatkanku akan Allah. Yakni, melihat/mendengar/membaca: Quran, Ilmu. Hal inilah yang akan menjadi ‘shockbreaker’ penjaga bilamana iman turun agar tak lama turunnya dan bisa melesat lagi. Menjadi pemicu agar amalku tetap dalam koridor kebaikan.Yah, secara teori seperti itu. Nyatanya hal ini sangat berat dilakukan. Butuh latihan panjang.
Begitulah penjalananku sejauh ini dalam membersamai al-‘Ashr. Bersyukur sekali Allah menggariskanku bergelut dengan ayat-ayatnya ini dan mendapatkan hikmah di dalamnya. Aku yakin yang sudah aku sentuh dari al-‘Ashr ini hanya bagian terluar dari permukaanya. Masih cetek. Masih ada misteri yang harus terus ku gali di dalamnya. Kalu memang ada kebenaran dalam tulisan ini, itu datangnya dari Allah. Sementara bila ada silap, itu semata-mata atas kerdilnya ilmuku. Dengan menuliskan pengalamanku ini, semoga saja teman-teman pembaca sekalian bisa share juga pengalamannya dalam merenungi dan berusaha mengamalkannya.
Oh my Rabb, ternyata kesimpulannya kepanjangan juga 😀
Yoweis lah, mudah-mudahan ada kesempatan waktu dan kesehatan untuk menuliskan perjalananku dengan bagian keduanya: “tawaa shaubil haq, tawaa shaubish shabr.”
Allahummarhamna bil Quraan..